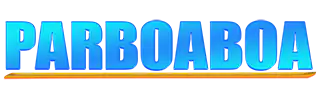PARBOABOA, Jakarta – Setiap tanggal 2 Mei, ada satu nama yang tak pernah absen dari ingatan bangsa, yaitu Ki Hadjar Dewantara.
Di balik nama itu, tersimpan semangat pendidikan yang tak pernah padam. Ia bukan sekadar tokoh sejarah, tetapi cahaya yang terus menyinari arah pendidikan Indonesia hingga hari ini.
Hari Pendidikan Nasional pun menjadi ruang kolektif untuk mengenang perjuangannya sekaligus mengukur kembali sejauh mana kita telah berjalan dalam cita-cita pendidikan bangsa.
Tahun ini, Hari Pendidikan Nasional kembali diperingati dengan semangat baru melalui tema “Partisipasi Semesta Wujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua.”
Tema ini disampaikan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, lewat Surat Edaran resmi yang ditandatangani pada 24 April 2025.
Di dalamnya terkandung ajakan untuk tidak menyerahkan pendidikan hanya pada sekolah dan pemerintah. Semua pihak—guru, siswa, orang tua, komunitas, hingga dunia usaha—diminta ikut andil menciptakan sistem pendidikan yang inklusif, adil, dan berkualitas.
Namun ajakan ini tak datang di ruang hampa. Ia muncul bersamaan dengan kenyataan bahwa dunia pendidikan Indonesia masih diliputi berbagai persoalan yang rumit dan kompleks.
Peneliti Sosiologi Pendidikan di BRIN, Anggi Afriansyah, memetakan setidaknya beberapa masalah besar yang hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah bersama.
Masalah pertama adalah soal akses, inklusivitas, dan kesetaraan. Menurut Anggi, ini adalah persoalan klasik yang belum tuntas.
Anak-anak dari keluarga miskin, terutama yang berada di daerah terpencil, kata dia, kerap menghadapi hambatan besar untuk masuk ke sistem pendidikan.
"Minim informasi, mahalnya biaya, dan terbatasnya fasilitas pendukung membuat pendidikan terasa jauh dari jangkauan," kata Anggi dalam sebuah keterangan belum lama ini.
Ia menekankan perlunya peran aktif pemerintah untuk hadir mendampingi kelompok-kelompok marginal ini, agar pendidikan menjadi ruang aman dan membebaskan, bukan sumber rasa takut dan minder.
Masalah berikutnya adalah kekerasan dalam dunia pendidikan, termasuk perundungan dan kekerasan seksual. Menurut Anggi, persoalan ini tidak pandang bulu. Dari sekolah elite hingga pesantren, dari lembaga pendidikan tinggi kedokteran hingga sekolah internasional, semua bisa menjadi lokasi terjadinya kekerasan.
Ia menyayangkan masih adanya kesenjangan besar antara aturan yang tertulis dan pelaksanaan nyata di lapangan. Ketika orientasi pendidikan belum sepenuhnya menempatkan kemanusiaan sebagai inti, maka kasus-kasus seperti ini akan terus berulang.
Di saat yang sama, tantangan literasi juga belum mampu dipecahkan. Harga buku yang tinggi menjadi penghalang utama bagi banyak keluarga untuk menumbuhkan budaya membaca di rumah.
Membangun kebiasaan membaca, kata Anggi, butuh proses panjang yang melibatkan keteladanan, dukungan komunitas, dan intervensi negara. Apalagi di era digital ini, ketika informasi bertebaran tanpa filter, kemampuan literasi menjadi semakin krusial.
Apalagi, data dari Kementerian Komunikasi dan Digital menyebutkan bahwa kurang dari separuh masyarakat Indonesia terbiasa memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya.
Masalah tak berhenti sampai di situ. Kesenjangan antara dunia pendidikan dan dunia kerja juga menjadi sorotan. Di tengah fenomena deindustrialisasi, lapangan kerja semakin sempit, tetapi pemberi kerja justru kesulitan menemukan anak muda yang memiliki keterampilan sesuai kebutuhan. Pendidikan dinilai belum mampu menyiapkan lulusan yang benar-benar siap pakai. Ini menciptakan lingkaran persoalan baru dalam upaya mengurangi angka pengangguran.
Di sisi lain, para guru yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam pembentukan karakter dan ilmu—masih bergelut dengan persoalan kesejahteraan. Banyak guru hidup dalam ketidakpastian, baik dari sisi ekonomi, rasa aman, maupun kesejahteraan mental.
Janji-janji peningkatan kesejahteraan sering kali hanya tinggal janji. Padahal, tantangan guru dalam memahami personalisasi siswa membutuhkan kondisi kerja yang mendukung. Tanpa perubahan sistem pendidikan dan keberpihakan kebijakan, sulit membayangkan munculnya guru-guru hebat.
Semua persoalan ini semakin pelik ketika disandingkan dengan arah kebijakan pendidikan nasional yang sering kali gamang. Menurut Anggi, dalam dua dekade terakhir, arah pendidikan di Indonesia berjalan maju mundur tanpa peta jalan yang jelas.
Setiap periode membawa agenda baru tanpa kesinambungan dari kebijakan sebelumnya. Ini melahirkan kebijakan tambal sulam yang justru menghambat pencapaian visi jangka panjang. Pendidikan, menurutnya, tidak bisa diatur dengan masa jabatan lima tahunan. Ia adalah proyek panjang, lintas generasi.
Di tengah segala tantangan itu, nama Ki Hadjar Dewantara kembali hadir dengan pemikiran dan warisan yang tetap relevan. Setelah kembali dari pengasingan tahun 1919, ia mendirikan Nationaal Onderwijs Instituut Taman Siswa pada 3 Juli 1922 di Yogyakarta.
Taman Siswa berdiri sebagai bentuk perlawanan terhadap sistem pendidikan kolonial yang elitis dan diskriminatif. Di tempat itu, anak-anak Indonesia diajarkan untuk menjadi manusia merdeka—secara pikiran, jiwa, dan budaya.
Ki Hadjar memperkenalkan pendekatan pendidikan yang holistik. Ia menolak pendidikan yang hanya mengejar nilai atau gelar. Baginya, pendidikan harus menyentuh aspek intelektual, emosional, sosial, dan spiritual.
Ia juga memperjuangkan pendidikan yang berpusat pada anak. Setiap anak diberi ruang untuk tumbuh sesuai potensi dan minatnya, bukan dipaksa mengikuti standar seragam yang mematikan kreativitas.
Prinsip terkenalnya—Ing ngarsa sung tulada, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani—menjadi fondasi yang tak lekang oleh waktu. Seorang guru harus mampu memberi teladan di depan, membangkitkan semangat di tengah, dan memberikan dorongan dari belakang. Prinsip ini hingga kini masih menjadi pegangan utama dalam filosofi pendidikan nasional.
Taman Siswa berkembang pesat dan menjadi inspirasi bagi berbagai lembaga pendidikan di Indonesia. Tak sedikit tokoh penting bangsa, seperti Soekarno, Mohammad Hatta, hingga Sutan Sjahrir, merasakan pengaruh besar dari pemikiran Ki Hadjar.
Atas jasa-jasanya, ia diangkat sebagai Menteri Pendidikan pertama Republik Indonesia dan diberi gelar Pahlawan Nasional setelah wafat pada 26 April 1959.
Pemikiran Ki Hadjar Dewantara menjadi sangat relevan di tengah zaman yang serba cepat ini. Di era globalisasi dan teknologi, pendidikan dituntut lebih adaptif, tapi tetap berakar.
Ia harus membentuk manusia yang tidak hanya cerdas, tapi juga berkarakter. Pendidikan bukan sekadar mencetak tenaga kerja, melainkan mencetak manusia seutuhnya—yang kreatif, kritis, dan memiliki kepekaan budaya.
Maka, peringatan Hari Pendidikan Nasional bukan hanya soal mengenang masa lalu. Ia adalah cermin besar bagi kita semua untuk melihat ke dalam, menilai, dan memperbaiki.
Pendidikan adalah tanggung jawab bersama. Dan seperti yang selalu diajarkan oleh Ki Hadjar, tugas kita bukan hanya mengajar, tetapi mendidik. Bukan sekadar membentuk kepala yang pintar, tetapi hati yang luhur.