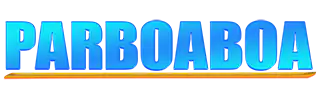PARBOABOA, Pematangsiantar – Di Pematangsiantar musik tumbuh bukan dari sekolah atau industri melainkan dari garasi, kamar sempit, atau ruang keresahan sehari-hari. Beberapa band memilih menyanyikan cerita kampung dengan bahasa lokal. Yang lain meneriakkan kritik sosial dalam distorsi tanpa kompromi. Genre berbeda tapi semangatnya sama: berdiri sendiri tanpa skema dukungan yang mapan.
Di kota yang lebih sering diam terhadap kreativitas anak mudanya ini musik menjadi jalan perlawanan. Empat band dari Pematangsiantar menolak ikut arus: mereka membangun identitas, meneriakkan keresahan, dan tetap setia pada akar meski tak ada jaminan panggung. Musik, bagi mereka bukan jalan pintas menuju ketenaran. Ini tentang perlawanan. Ihwal melawan diam, melawan standar industri, melawan negara yang hanya datang saat membutuhkan.
Punxgoaran, dengan punk dan logat Batak-nya, menyanyikan kegelisahan rakyat kecil. Bloodnesia menggeram lewat distorsi dan menciptakan ruang ekspresi yang ditolak kota. Paku Mati yang bertahan sejak 1997 mendobrak kebekuan komunitas metal agar tak jadi fosil. Siantar Rap Foundation (SRF) memadukan hiphop dan Batak.
Empat band dari Pematangsiantar bukan sekadar pembawa genre berbeda melainkan representasi cara pandang yang beragam terhadap musik, komunitas, dan relasi dengan kekuasaan.
Punxgoaran, misalnya, memposisikan diri sebagai suara alternatif yang menolak tunduk pada pola relasi semu antara musisi dan pemerintah. Bagi mereka, musik adalah medium keberpihakan: kepada kampung halaman, bahasa, dan komunitas marjinal. Sikap independennya bukan sebatas gaya melainkan strategi bertahan dalam sistem yang tidak adil. Konsistensi personel dan penolakan terhadap star syndrome menjadi garis ideologis yang mereka pegang. Mereka bukan mencari panggung, tapi menciptakan pentas sendiri meski dengan risiko dikucilkan dari ruang-ruang resmi.
Siantar Rap Foundation punya jalan yang berbeda. Tetap berakar pada kemandirian, mereka membangun sistem sendiri sejak awal. Dari studio produksi, distribusi rilisan, hingga manajemen internal dibangun sendiri. Meski tidak vokal dalam kritik sosial, SRF menunjukkan bahwa musik bisa menjadi warisan budaya tanpa harus menjadi alat perlawanan. Mereka memilih jalur profesional yang bersih dari relasi transaksional.
Mereka meraih pengakuan lewat konsistensi dan kualitas produksi. Di tengah ketidakpastian ekosistem musik lokal, mereka adalah bukti bahwa kolektivitas dan struktur internal bisa menciptakan daya tahan yang kuat tanpa bergantung pada komunitas eksternal yang sering kali rapuh.
Adapun Bloodnesia, mereka mewakili semangat bertahan di tengah kehancuran infrastruktur musik lokal. Mereka muncul saat semangat komunitas nyaris mati dan regenerasi mandek. Dalam konteks seperti itu, eksistensi mereka adalah bentuk perlawanan tersendiri.

Mereka sadar tidak sedang bersaing untuk panggung nasional, tetapi mempertahankan ruang ekspresi yang makin sempit di kota sendiri. Kemandirian teknis mereka terbatas tetapi ditambal dengan kegigihan dan prinsip: tidak menyesuaikan diri dengan pasar, tidak ikut arus, dan tidak tunduk pada stigma. Di antara banyak band metal yang memilih diam, Bloodnesia tetap menyuarakan bahwa musik keras punya tempat yang sah dalam lanskap budaya lokal.
Sementara itu, Paku Mati berdiri sebagai sumbu sejarah. Mereka adalah pengingat bahwa musik metal di Siantar pernah hidup, mati, lalu dibangkitkan kembali oleh tangan-tangan yang sama. Mereka tidak hanya bermain musik, tapi juga membangun komunitas, mencetak rilisan, dan menjadi institusi informal bagi regenerasi. Mereka tidak banyak bicara soal dukungan pemerintah,

karena dari awal mereka tahu itu tidak akan datang. Yang mereka lawan bukan hanya arus pasar, tetapi juga lupa kolektif: lupa bahwa kota ini pernah punya suara keras yang tak teredam. Kini, ketika usia tak lagi muda, mereka tetap turun tangan menyambungkan generasi sebuah kerja budaya yang tidak tampak di panggung, tapi vital bagi keberlanjutan.
Identitas Lokal
Guido Hutagalung, vokalis Punxgoaran, bukanlah lulusan sekolah musik atau bagian dari ekosistem seni mapan. Bersama rekan-rekannya, ia memulai band dari keresahan dan semangat untuk bersuara, bukan karena fasilitas atau modal besar.
"Kami bukan akademisi, hanya orang-orang yang ingin bermusik dan tampil apa adanya," ujarnya.
Dalam dunia musik nasional yang banyak dijejali kemasan sensasional, Punxgoaran memilih jalan sebaliknya: menyuarakan keresahan lokal dengan bahasa kampung. Lagu seperti Sayur Kol, yang awalnya hanya pengisi album justru meledak dan menjadi lagu ikonik mereka. Lirik sederhana, musik keras, dan pesan sehari-hari menjadi senjata utama mereka. Identitas Batak bukan tempelan, tapi nafas utama dalam lagu-lagu seperti Mangan Modom, Taridem-Idem, hingga Stevenson Oi.
Guido selalu bertanya sebelum menulis lagu. "Untuk siapa lagu ini diciptakan?" Jawabannya adalah Siantar.

Nama Punxgoaran sendiri berasal dari "punk" dan "panggoaran". Yang terakhir ini sebutan orang Batak Toba untuk anak sulung. Nama itu adalah filosofi: menjadi yang pertama bersuara untuk keluarga, komunitas, dan budaya yang membesarkan mereka.
Sikap itu juga tampak dalam kritik sosial yang mereka sampaikan. Guido tidak segan membuat lagu untuk masyarakat adat Sihaporas yang sedang berkonflik dengan korporasi perusak alam milik taipan asal Medan Sukanto Tanoto PT Toba Pulp Lestari (PT TPL). Bahkan ketika video klipnya dicegat langsung oleh pihak perusahaan dan mereka diserang buzzer di media sosial, Guido tetap berdiri tegak.
"Musik kami bukan untuk pejabat, tapi untuk rakyat," katanya. Konsekuensinya? Mereka tak diundang lagi ke acara resmi. Bahkan saat lagunya diputar di acara air mancur Waterfront Pangururan, mereka tetap harus membayar tiket masuk.
SRF pun mengolah hiphop dengan pendekatan yang serupa. Lagu Dainang menjadi titik balik, membawa mereka dikenal luas karena berhasil menyentuh sisi emosional pendengar Batak urban. Nama SRF kemudian naik tajam, dengan pendengar hampir 300 ribu per bulan di Spotify. Album mereka berisi 8 hingga 12 lagu dirilis konsisten, baik dalam bentuk CD (hingga 1.200 keping) maupun digital di YouTube, Spotify, dan Joox.
Mereka merekam di studio milik produser internal, Awenz, demi menjaga kemandirian dan karakter unik.
"Awalnya kami pikir Dainang ya bakal begitu aja. Tapi justru itu yang buat kami booming," kata Alfred.
Prinsip mereka jelas: karya adalah panggung, bukan koneksi. Bahkan soal fee pun menyesuaikan skala acara. SRF memilih tetap berdiri tanpa berharap ke pemerintah. Rezeki sudah ada takarannya. Karya itu sendiri yang akan mencari rezekinya. Begitu menurut mereka.
Punxgoaran dan SRF menolak relasi semu dengan kekuasaan. Mereka ingin panggung dibuka karena karya, bukan karena dekat dengan pejabat.
Guido pernah mengkritik Pemkot Siantar yang menghabiskan Rp 150 juta untuk band nasional saat hari ulang tahun kota. "Dengan rate hingga di atas Rp150 juta, kita bisa hidupkan musisi lokal dan UMKM. Ini bukan soal uang, tapi soal kebanggaan."
Namun, tidak semua musisi berada pada jalur yang sama dalam meraih sorotan publik. Di tengah tren musik yang menjual identitas lokal, band seperti Bloodnesia justru tetap memilih jalur metal dengan narasi keras dan karakter kuat. Tapi eksistensi mereka tidak selalu diterima di panggung resmi atau percakapan media lokal.
“Kalau dilihat, dari dulu kita nggak pernah dikasih panggung sama pemerintah. Jadi, kita sudah terbiasa nggak diundang. Karena kita bukan musik aman,” ucap Ashri Sembiring.
Ia menyadari bahwa genre mereka yang keras, penuh distorsi, dan berbicara soal realitas pahit tidak dianggap layak tampil dalam panggung yang diatur oleh protokol, sponsor, atau agenda politik. Bagi mereka, tidak tampil bukan karena tak layak, tapi karena tidak cocok dengan narasi arus utama yang hanya memberi ruang bagi musik yang "aman" dan mudah dicerna. (Bersambung)
Editor: P. Hasudungan Sirait
Catatan: Tulisan ini merupakan karya kelompok peserta Sekolah Jurnalisme Parboaboa (SJP) Pematangsiantar, Batch 2. SJP merupakan buah kerja sama Parboaboa.com dengan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia.