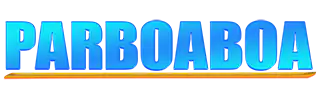Tulisan-3
PARBOABOA, Pematangsiantar – Di sudut sebuah lapo [kedai] kecil di Siantar merebak aroma tuak segar yang baru saja dituangkan ke dalam gelas bening. Benny Tambak—pegiat budaya sekaligus penikmat tuak sejak muda—duduk santai di bangku kayu. Matanya menyorot raut wajah kawan-kawan yang sedang berbincang hangat di sekitarnya.
Percakapan ihwal apa saja: keluarga, dinamika sosial di kampung, hingga politik nasional dan internasional. Sungguh, di tempat seperti inilah suara-suara yang sering terpinggirkan menemukan ruangnya. Ditemani tuak, perbincangan niscaya bertambah seru.
“Tuak itu bukan hanya soal rasa,” ujar Benny Tambak pelan, “tapi juga tentang bagaimana kita menjaga ruang bicara yang jujur dan kesetaraan di tengah masyarakat.”
Aktif memperkenalkan kembali tuak di tengah derasnya arus modernisasi, ada satu kalimat yang selalu ia bawa ke mana pun: “Tuak from God.”
Kalimat itu bukan sekadar ucapan iseng atau slogan promosi. Ia adalah wujud keyakinan mendalam bahwa minuman yang satu ini bukan hanya hasil fermentasi alam melainkan karunia yang menyimpan makna: datang dari alam sebagai pemberian Tuhan sehingga pantas untuk dinikmati.
“Tuak itu bukan racun, asal tahu cara meminumnya. Ini bukan sekadar minuman, tapi media yang mempertemukan orang, menjembatani obrolan, sekaligus merawat nilai-nilai kita,” tutur Benny, yang selama bertahun-tahun rutin menggelar diskusi, pertunjukan budaya, dan festival kecil dengan tuak sebagai pengikatnya.
“Kalau kopi punya warung kopi, kenapa tuak tidak boleh punya ruang yang layak?” tanyanya pada satu malam di salah satu lapo favoritnya. “Kita butuh ruang—bukan untuk mabuk-mabukan, tapi untuk mendengar dan didengar. Tuak hanyalah perantara.”
Lebih dari sekadar minuman, menurut dia, tuak mengandung nilai simbolik tinggi: sumber semangat sekaligus lambang keakraban. Dan, dalam konteks adat, minuman ini hadir dalam posisi sakral di pelbagai perhelatan. Mulai dari pesta pernikahan hingga mangongkal holi [menggali tulang-belulang leluhur untuk dipindahan ke tugu keluarga].
Meruntuhkan Stigma
Ketertarikan Benny pada tuak muncul sejak ia masih remaja. Ia tumbuh di wilayah sentra pohon aren, tempat sebagian besar penduduk bekerja sebagai paragat [penderes tuak]. Awalnya ia hanya ikut-ikutan mencicipi demi suasana. Namun, lama-kelamaan ia menyukainya—bukan karena candu, melainkan karena minuman tersebut telah menjadi bagian dari irama sosial dan budaya.
Kini, bukan hanya penikmat. Dia juga ikut menjual, menyuguhkan, dan sekaligus menyulap ruang minum menjadi ruang berpikir. Langkah itu tidak mudah. Ia harus meruntuhkan stigma. Ia mengemas tuak dengan cara baru tanpa menghilangkan rasa aslinya. Ia bekerja sama langsung dengan paragat, memastikan proses penyadapan berjalan alami dan etis, serta membeli dari mereka lalu menjual ke berbagai tempat.
Dalam pengamatan Benny, saat ini kalangan mudalah kelompok terbesar peminum tuak di berbagai lapo. Bagi mereka, tuak adalah alternatif paling pas. Bukan semata karena kandungan alkoholnya, melainkan karena akses yang mudah dan harga yang jauh lebih terjangkau dibanding minuman kemasan beralkohol.
Meski harga tuak telah berubah, dari Rp1.500 dulu menjadi Rp3.000 per gelas, itu tetap saja masih murah. Proses menikmatinya pun praktis: cukup singgah ke lapo terdekat, duduk, lalu meneguknya dalam suasana akrab. Kombinasi harga ramah kantong dan atmosfer menjadikannya pilihan utama untuk melepas penat, menjalin pertemanan, atau sekadar mengisi waktu luang.
Fenomena ini menandakan bahwa tuak tidak hanya bertahan sebagai minuman tradisional tetapi juga berhasil menarik minat generasi muda dan menemukan tempatnya dalam gaya hidup mereka saat ini.
Bagi Benny, tuak melampaui wujudnya sebagai minuman. Dalam kebudayaan Batak, ia menjadi simbol kebersamaan, jejak identitas yang diwariskan turun-temurun, dan jembatan relasi sosial. Juga, teman dalam obrolan sederhana hingga percakapan komunitas yang penuh makna.
Simpul Sosial
Dalam masyarakat Batak, tuak memiliki dimensi mitologis yang mendalam. Dikisahkan seorang gadis miskin yang harus menjadi istri kelima seorang juragan kaya untuk melunasi utang keluarganya. Ia menolak takdir itu dengan berkata: "Jika aku mati, jangan kuburkan jasadku. Aku akan menjadi pohon yang bermanfaat sepanjang masa."
Setelah ia meninggal, tumbuhlah pohon aren—sumber air nira untuk tuak. Air yang menetes dari batangnya dipercaya sebagai air mata sang gadis, penanda cinta dan pengorbanan abadi.
Kini, tuak menjelma menjadi bagian dari tren dan gaya hidup tanpa kehilangan akar budayanya. Meski stigma negatif masih ada, penting diingat bahwa ia berasal dari alam—pemberian Tuhan. Ia menjadi teman bersantai sekaligus penghangat suasana.
Soal rasa, tentu itu subjektif dan bergantung selera. “Bagi saya, tuak yang enak adalah yang terasa sodanya—karbonasi alami dari fermentasi yang pas, menyegarkan dan ringan,” kata Banny Tambak. Jika ditambah raru (kulit kayu pahit), cita rasanya berubah lebih kuat, berkarakter, dan memberi kedalaman kompleks yang disukai penikmat berpengalaman.
Selain alami, tuak juga unggul secara ekonomi. Harganya jauh lebih terjangkau dibanding teh, kopi, atau minuman beralkohol modern. Cita rasanya yang kuat dan aroma tajam menjadikannya tak mudah dilupakan.
Dalam budaya Batak, lapo menjadi arena marmitu—minum tuak sambil bernyanyi dan berbagi cerita. Suasana ini menciptakan keakraban hangat, tempat segala hal bisa dibicarakan dengan terbuka. Bahkan dalam momen pemilihan kepala desa, kedai ini sering berubah menjadi ruang kampanye informal yang menjembatani komunikasi antara pemimpin dan rakyat, tanpa sekat protokoler.
Lapo, atau pakter tuak, pada akhirnya bukan sekadar tempat menikmati minuman tradisional. Ia adalah ruang penting yang meruntuhkan sekat-sekat sosial. Di sini, tak penting usia, profesi, atau status ekonomi—semua bisa duduk di meja yang sama, mengangkat gelas, dan berbicara dari hati ke hati.
Sebagai salah satu tokoh yang aktif memperkenalkan kembali tuak dalam format lebih modern dan terbuka, Benny percaya berpendapat bahwa lapo itu simpul sosial yang tak boleh hilang. Lewat inisiatif komunitas dan festival, ia bersama rekan-rekannya berupaya merawat tradisi tua ini agar tak lekang ditelan zaman.

Ia lantas berpesan, terutama kepada generasi muda, agar melestarikan tuak. Langkahnya dapat dimulai dari yang sederhana namun bermakna.
Pertama, menciptakan wadah yang layak—seperti lapo, warung, atau kafe—dengan konsep terbuka dan inklusif. Bukan sekadar tempat menjual tuak, tetapi titik temu budaya dan ruang perjumpaan lintas generasi.
Kedua, memanfaatkan media sosial untuk promosi: lewat video pengenalan, dokumentasi proses pembuatan, atau kisah-kisah tradisi yang dibagikan di Instagram, TikTok, YouTube, dan yang lain.
Ketiga, menyelenggarakan festival budaya, seperti Tuak Fest 2014, yang mempertemukan para pegiat dari berbagai wilayah. Cara ini memperkuat kesadaran kolektif tentang pentingnya menjaga tradisi lokal.
Dalam pikiran Benny, tuak bukan sekadar cairan fermentasi—melainkan jembatan antara masa lalu dan masa depan, antara suara yang nyaring dan suara yang kerap luput terdengar. Di lapo, ia menemukan ruang paling jujur untuk menjadi manusia—ruang di mana semua orang duduk setara, berbicara apa adanya, dan merasa didengar.
Di antara gelas-gelas kecil yang tak pernah benar-benar kosong, Benny Tambak merawat sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar minuman: ia menjaga warisan, membangun ruang, dan menanamkan makna. (Tamat)
Penulis: Novriani Tambunan, Indah Cahyani, Alberto Nainggolan—peserta Sekolah Jurnalisme Parboaboa (SJP) Pematangsiantar, Batch 2. SJP merupakan buah kerja sama Parboaboa.com dengan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia).
Editor : P. Hasudungan Sirait