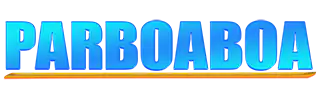PARBOABOA, Jakarta – Pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur, meskipun telah diatur oleh undang-undang, masih terus terjadi di berbagai penjuru negeri. Umumnya, kasus ini banyak dijumpai di daerah terpencil, dan penyebabnya pun beragam.
Padahal, menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1), usia minimal menikah baik bagi perempuan maupun laki-laki adalah 19 tahun. Sayangnya, realita di lapangan masih jauh dari harapan.
Berdasarkan data yang dihimpun dari berbagai sumber, tercatat bahwa delapan provinsi di Indonesia memiliki persentase pernikahan dini yang cukup tinggi, menunjukkan kondisi yang memprihatinkan terkait perlindungan anak dan remaja.
Provinsi dengan angka pernikahan dini tertinggi adalah Nusa Tenggara Barat (NTB), yang mencatat angka mencapai 16,23 persen pada tahun 2022.
Angka ini hampir dua kali lipat dari rata-rata nasional yang berada di kisaran 8,06 persen. Data ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA).
Selanjutnya, Kalimantan Tengah juga menjadi salah satu provinsi dengan angka pernikahan dini yang tinggi.
Pada tahun 2020, persentasenya mencapai 16,35 persen, kemudian menurun secara bertahap menjadi 15,47 persen pada 2021, dan 14,72 persen pada 2022. Meski tren menunjukkan penurunan, angkanya tetap tergolong tinggi karena banyak remaja menikah sebelum usia 18 tahun.
Gorontalo memperlihatkan tren yang fluktuatif. Pada tahun 2020, angka pernikahan dini di provinsi ini berada di angka 14,73 persen, turun ke 11,64 persen di 2021, namun kembali naik menjadi 13,65 persen pada tahun 2022.
Sementara itu, Kalimantan Barat mencatatkan angka 17,14 persen pada tahun 2020. Angka tersebut kemudian menurun menjadi 13,84 persen pada 2021, dan terus menurun menjadi 12,84 persen di tahun 2022.
Provinsi Sulawesi Tengah mengalami penurunan dari angka 14,89 persen pada 2020 menjadi 12,51 persen pada 2021. Namun, pada 2022 terjadi kenaikan kecil menjadi 12,65 persen.
Di Sulawesi Barat, data hingga Mei 2023 menunjukkan angka pernikahan dini berada di 11,7 persen. Ini menunjukkan penurunan yang cukup signifikan dibandingkan tahun 2020 yang sempat mencapai 17,71 persen.
Jawa Timur juga mencatat angka pernikahan dini yang cukup tinggi. Pada tahun 2022, tercatat sebesar 10,44 persen remaja menikah di usia dini. Bahkan, terdapat lebih dari 15.000 permohonan dispensasi nikah di provinsi ini sepanjang tahun tersebut.
Terakhir, Jawa Barat menunjukkan penurunan konsisten dalam angka pernikahan dini. Dari 10,35 persen pada tahun 2020, angka tersebut menurun menjadi 9,23 persen di 2021, dan kembali turun ke angka 8,06 persen di tahun 2022. Wilayah yang paling banyak menyumbang angka tersebut antara lain Cirebon, Garut, dan Sukabumi.
Sedangakan dalam hitungan global yang diterbitkan oleh UNICEF 2023, sebanyak 25,53 juta perempuan di Indonesia menikah sebelum usia 18 tahun.
Fakta ini menempatkan Indonesia di peringkat keempat dunia, setelah India, Bangladesh, dan Cina.
Sementara itu, Indonesia Judicial Research Society (IJRS) mencatat bahwa 95% permohonan dispensasi kawin dikabulkan oleh pengadilan pada rentang waktu 2019–2023. Mirisnya, sepertiga alasan permohonan tersebut adalah karena kehamilan di luar nikah.
Pemicu Pernikahan Dini
Salah satu pemicu utama pernikahan dini adalah tekanan ekonomi keluarga. Dalam keluarga yang hidup dalam kondisi serba kekurangan, anak perempuan sering kali dianggap sebagai beban ekonomi tambahan.
Maka, menikahkan anak dianggap sebagai cara untuk meringankan beban keluarga, sekaligus memberikan tanggung jawab tersebut kepada keluarga suami.
Ini adalah bentuk "survival strategy" yang sering terjadi di wilayah miskin, terutama di pedesaan atau kawasan dengan akses terbatas terhadap sumber daya.
Selain faktor ekonomi, minimnya pendidikan juga menjadi penyebab yang tak kalah penting. Anak-anak yang putus sekolah atau tidak mendapatkan pendidikan yang layak cenderung tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang dampak jangka panjang dari pernikahan dini.
Mereka mungkin tidak tahu bahwa pernikahan di usia muda dapat berdampak buruk pada kesehatan reproduksi, psikologis, serta masa depan mereka secara keseluruhan, termasuk peluang kerja dan kemandirian finansial.
Kemudian, adat dan norma sosial di beberapa daerah masih sangat kuat mempengaruhi pandangan masyarakat tentang pernikahan.
Ada anggapan bahwa menikah muda adalah bagian dari tradisi yang harus dijalani. Dalam budaya tertentu, perempuan yang telah mencapai usia remaja dianggap sudah "siap" menikah, meskipun secara psikologis dan biologis mereka belum matang. Norma ini sering diperkuat oleh tokoh masyarakat atau agama yang menganggap pernikahan dini sebagai bentuk perlindungan terhadap pergaulan bebas.
Tak kalah penting, kehamilan di luar nikah juga menjadi alasan banyak pernikahan dini terjadi secara mendadak.
Dalam masyarakat yang memegang teguh nilai-nilai moral, kehamilan di luar pernikahan dianggap sebagai aib keluarga yang harus segera "ditutupi" dengan pernikahan.
Hal ini biasanya dilakukan tanpa mempertimbangkan kesiapan pasangan, yang bisa berujung pada konflik, perceraian dini, atau kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis.
Terakhir, tekanan dari lingkungan, baik dari keluarga besar maupun masyarakat sekitar, juga memainkan peran penting.
Anak perempuan sering kali mendapatkan tekanan dari orang tua untuk segera menikah agar tidak menjadi "perawan tua", atau untuk mengikuti jejak teman-temannya yang sudah menikah.
Dalam situasi seperti ini, anak menjadi korban dari sistem sosial yang memaksa mereka untuk mengambil keputusan besar dalam hidup tanpa kesiapan yang memadai.
Perlu Aksi Nyata
Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, menekankan bahwa upaya pencegahan pernikahan dini tidak hanya soal regulasi.
Diperlukan pemahaman bersama antara pemangku kebijakan dan masyarakat agar kebijakan yang ada bisa berjalan efektif.
"Sejumlah kebijakan sudah tersedia, yang dibutuhkan sekarang adalah pemahaman dan implementasi," ujar Lestari, Selasa (14/1/2025).
Lestari, yang juga dikenal dengan sapaan Rerie, menyebut pernikahan dini sebagai bentuk kekerasan terhadap anak. Dampaknya tidak hanya fisik, tapi juga mental, sosial, dan seksual.
Ia menegaskan pentingnya edukasi hak-hak reproduksi perempuan secara berkelanjutan agar kebijakan yang telah ada bisa memberikan dampak nyata.
"Kita butuh generasi penerus yang sehat, berkarakter, dan mampu bersaing di tengah tantangan global," ujarnya.