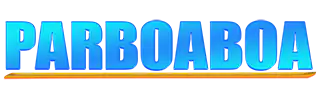PARBOABOA, Jakarta - Langkah pemerintah Indonesia mengusulkan perubahan batas kawasan Tropical Rainforest Heritage of Sumatra (TRHS) ke UNESCO memantik perdebatan.
Bagi aktivis lingkungan, terutama Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), kebijakan ini bukan sekadar persoalan teknis batas wilayah, melainkan babak baru dari praktik kolonialisme sumber daya yang kini berwajah hijau—bernama energi terbarukan.
Rencana pemerintah untuk melakukan delineasi atau penetapan ulang batas Hutan Hujan Tropis Warisan Sumatra (TRHS) tidak mengejutkan bagi Jaringan Advokasi Tambang (Jatam).
Bagi mereka, usulan yang diajukan ke UNESCO itu hanyalah langkah awal untuk membuka pintu eksploitasi baru terhadap sumber daya alam di kawasan konservasi.
Terlebih, di balik jargon transisi energi dan swasembada listrik, Jatam melihat adanya upaya memperluas pasar kekuasaan dengan cara merampas energi alami yang selama ini menopang kehidupan masyarakat lokal.
“Lagi-lagi, warga yang menjadi korban atas praktik banal dari kekuasaan,” ujar Juru Kampanye Jatam, Alfarhat Kasmandia, di Jakarta, Jumat, 3 Oktober 2025.
Ia menilai, delineasi di kawasan Suoh dan Sekincau, yang terletak di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, Lampung Barat, menjadi bukti nyata bagaimana kolonialisme ekstraktif negara kini berlangsung dalam wajah baru: eksploitasi yang dibungkus dengan narasi pembangunan hijau.
Menurut Alfarhat, akar dari polemik ini sudah tertanam sejak pemerintah mulai mengutak-atik regulasi demi melancarkan agenda ekstraksi panas bumi.
Penerbitan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi, yang menggantikan UU Nomor 27 Tahun 2003, menjadi pintu pembuka.
Regulasi baru ini mengeluarkan usaha panas bumi dari kategori industri pertambangan, yang secara otomatis melonggarkan batas hukum terhadap aktivitas eksplorasi di kawasan hutan produksi dan hutan lindung.
“Padahal, esensinya tetap sama—mengambil energi dari dalam perut bumi melalui proses ekstraksi yang intensif,” tegas Alfarhat.
UU tersebut memberi ruang legal bagi pengusahaan panas bumi di hutan konservasi melalui izin pemanfaatan jasa lingkungan, sebagaimana diatur dalam UU 41/1999 tentang Kehutanan. Perubahan ini, menurut Jatam, menegaskan orientasi ekonomi yang lebih berpihak pada investasi ketimbang kelestarian ekosistem.
Kebijakan makin melonggar ketika Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Menteri Nomor P.46/Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2016.
Aturan ini membuka ruang pemanfaatan panas bumi di kawasan konservasi, termasuk taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam.
Revisi peraturan pada 2019 bahkan memperluas definisi pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi tanpa menyebutnya sebagai aktivitas pertambangan.
“Padahal, untuk memanfaatkan panas bumi tetap dibutuhkan eksplorasi dan pengeboran, yang berarti ada proses ekstraksi sumber daya alam,” jelas Alfarhat.
Bagi Jatam, logika ini menyesatkan karena mengaburkan batas antara konservasi dan eksploitasi. Aktivitas pengeboran jelas berdampak terhadap ekosistem, baik melalui perubahan lanskap maupun gangguan terhadap biodiversitas dan sumber air.
Ironisnya, lanjut Alfarhat, legitimasi terhadap aktivitas ini semakin diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
Revisi terhadap UU Nomor 5 Tahun 1990 itu menegaskan bahwa pemanfaatan panas bumi termasuk dalam kategori jasa lingkungan, sejajar dengan ekowisata.
“UU ini memberi karpet merah bagi ekstraksi energi panas bumi di kawasan konservasi,” ujarnya.
Dengan dalih transisi energi bersih, negara dinilai sedang menormalisasi eksploitasi di wilayah yang seharusnya steril dari aktivitas industri.
Sementara itu, dari pihak pemerintah, argumentasi berbeda disampaikan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian Kehutanan, Satyawan Pudyatmoko.
Ia menegaskan bahwa delineasi yang diusulkan bukanlah bentuk pengabaian terhadap konservasi, melainkan penyesuaian berdasarkan kondisi aktual di lapangan.
“Kawasan Suoh dan Sekincau di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan sudah tidak memiliki karakteristik hutan alam,” ujarnya, Senin, 29 September 2025.
Menurut hasil pencermatan yang dilakukan, wilayah tersebut kini didominasi oleh permukiman dan kebun kopi milik warga.
Atas dasar itu, pemerintah menilai tidak lagi layak mempertahankan area tersebut dalam status Warisan Dunia.
Satyawan menyebut, rekomendasi delineasi sebenarnya sudah disarankan oleh Tim Uni Internasional untuk Konservasi Alam (IUCN) sejak 2018, dan diperkuat melalui mandat Komite Warisan Dunia (WHC) pada sidang ke-42 tahun 2019.
“Significant Boundary Modification ini justru untuk menjaga kredibilitas TRHS di mata dunia,” jelasnya.
Satyawan juga menepis kekhawatiran bahwa rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di wilayah tersebut akan merusak lingkungan.
Menurutnya, teknologi geotermal termasuk energi terbarukan yang ramah lingkungan, karena tidak menghasilkan emisi karbon tinggi dan hanya membutuhkan ruang operasi terbatas.
“Pembangunan dilakukan di zona pemanfaatan, dan kegiatan operasionalnya tidak mengganggu satwa liar,” katanya.
Namun, bagi aktivis lingkungan, klaim ramah lingkungan tidak cukup untuk menutupi kenyataan bahwa kawasan konservasi kembali menjadi target eksploitasi.
Apalagi, di tengah ambisi nasional mempercepat pembangunan infrastruktur energi hingga ke wilayah timur seperti Papua, pola pendekatan yang mengabaikan hak masyarakat adat dan ekosistem alam dikhawatirkan akan kembali berulang.
Menurut data Kementerian Investasi (BKPM), percepatan pembangunan di Papua dan daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) pada 2025 melibatkan proyek energi terbarukan senilai lebih dari Rp30 triliun, termasuk PLTA dan PLTP.
Jika kebijakan delineasi seperti di TRHS menjadi preseden, maka Papua pun berpotensi menghadapi ancaman serupa: eksploitasi atas nama energi hijau.