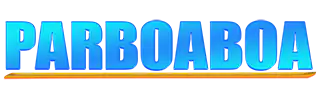Tulisan-3
PARBOABOA, Pematangsiantar – Opera Batak mungkin tak lagi hadir selama tiga malam berturut-turut di lapangan desa, atau memadati halaman hingga larut malam seperti dulu. Namun di tangan para pelestari, kesenian ini sedang menemukan bentuk baru.
Bentuk yang mungkin akan tampil sebagai drama musikal keluarga yang ringan, bakal merambah layar digital, atau tetap bertahan di panggung terbuka di tepi Danau Toba. Warga berkumpul bukan sekadar untuk menonton tetapi untuk merasakan kembali denyut budaya yang pernah menjadi bagian tak terpisahkan dari hidup mereka.
Salah satu orang yang paling memahami denyut itu adalah Rithaony Hutajulu, akademisi dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara (USU). Ia lahir di generasi yang tak pernah menyaksikan langsung masa kejayaan Opera Batak, namun cerita tentangnya didapatnya dari sang ayah. Malam-malam saat Opera Batak hadir di lapangan desa menjadi kisah yang diwariskan turun-temurun, cerita yang penuh warna dan kehangatan.
“Saya hanya bisa membayangkan dari cerita ayah saya bagaimana sebuah panggung bisa mempersatukan satu desa,” kenangnya dengan mata yang menerawang jauh.
Kecintaannya pada musik membawanya masuk ke jurusan etnomusikologi USU pada 1982. Di sana, ia bertemu dengan para pelaku Opera Batak yang masih aktif, mendengar langsung cerita-cerita dari orang-orang yang pernah hidup di tengah kejayaannya.

Ia memutuskan meneliti 79 lagu Opera Batak, menotasikannya, dan mengumpulkan dokumentasi dari sang maestro Tilhang Gultom yang merekam pertunjukan hingga dekade 1980-an. Dari penelitiannya, ia menemukan satu kesimpulan yang mengusik hatinya: Opera Batak masih ada, tetapi tak lagi bernyawa.
“Dulu Opera Batak bukan cuma hiburan tapi juga media komunikasi dan kritik sosial. Sekarang, semangat itu hampir hilang,” ujarnya dengan nada prihatin.
Bagi Rithaony, masa lalu Opera Batak adalah masa ketika panggungnya menjadi ruang untuk menyampaikan pesan, kritik sosial, dan refleksi kehidupan. Kisah Siboru Tumbaga misalnya, lahir dari kegelisahan tentang mengapa anak perempuan diperlakukan berbeda dari anak laki-laki. Setiap lakon bukan hanya cerita, tetapi cermin bagi masyarakat untuk melihat dirinya sendiri. Kini, ia melihat pertunjukan Opera Batak cenderung mengulang format lama tanpa sentuhan baru.
“Kalau hanya mempertahankan bentuk, tapi tidak membangkitkan rohnya, penonton akan cepat merasa bosan,” tambah istri musisi terkemuka almarhum Irwansyah Harahap.

Namun, Rithaony yang juga seorang performer percaya bahwa seni ini bisa kembali hidup jika berani berinovasi. Ia mencontohkan lewat karyanya, The Story Buku Ende, sebuah drama paduan suara yang melibatkan 135 pemain. Pementasan ini memadukan nyanyian dengan sedikit dialog, mengangkat kisah yang relevan dengan masyarakat namun tetap berpijak pada tradisi.
Upaya lain juga dilakukannya yakni membentuk sebuah grup musik yang bernama Mataniari. Di kelompok itu Ia bersama maestro-maestro batak lainnya membawakan kembali musik-musik tradisional dan musik Opera Batak versi orisinal karya Tilhang Gultom hingga versi aransemennya yang luar biasa memukau.
“Penonton itu mau datang kalau merasa kisahnya dekat dengan hidup mereka. Kuncinya relevansi, bukan sekadar mempertahankan tradisi,” tegasnya.
Pandangan tentang perlunya pembaruan juga datang dari budayawan asal Pematang Siantar, Sultan Saragih. Ia melihat Opera Batak kini berada di persimpangan: apakah akan menjadi artefak budaya yang hanya dikenang atau seni yang kembali hidup di tengah masyarakat.
“Opera Batak, kesenian yang dulu dicintai masyarakat tampak sedang redup bahkan di tengah komunitas Batak sendiri,” kata lelaki bersuara berat.
Generasi penonton lama yang dulu tumbuh di desa-desa sudah menua, sementara generasi baru hidup dalam dunia yang serba cepat, visual, dan interaktif. Mereka tidak otomatis merasa terhubung dengan format lama pertunjukan yang panjang dan berstruktur tradisional. Menurut Sultan, Opera Batak harus mampu bicara dengan bahasa visual modern tanpa mengorbankan jati diri.
“Saya bayangkan panggung Opera Batak dengan layar LED, visual interaktif, atau bahkan karakter dari kecerdasan buatan. Itu akan memikat generasi muda tanpa menghilangkan akarnya.”
Baginya, kebangkitan Opera Batak memerlukan ekosistem yang kokoh: pelestari budaya, dukungan pemerintah daerah, komunitas seni, hingga manajemen yang profesional.
“Kalau kita mengelola Opera Batak sebagai industri kreatif, bukan hanya kegiatan budaya musiman, ia bisa hidup dan memberi penghidupan bagi para pelakunya,” ujarnya penuh keyakinan.

Antropolog Avena Matondang memandang Opera Batak sebagai bukti kelenturan budaya Batak. Ia mengingatkan bahwa sejak awal, Opera Batak adalah hasil adaptasi dari opera bangsawan dan tonil yang kemudian diolah menjadi khas Batak.
“Budaya Batak itu lentur. Ia bisa mengadopsi unsur luar tanpa kehilangan dirinya,” jelasnya.
Namun, di era digital, seni pertunjukan ini harus bersaing dengan film, sinetron, dan beragam konten daring. Avena melihat peluang besar menjadikan Opera Batak sebagai media pendidikan budaya yang adaptif.
“Generasi muda butuh versi Opera Batak yang berbicara dengan bahasa mereka, entah lewat digitalisasi, tema kontemporer, atau cakupan cerita yang lebih luas.”
Namun ia menekankan pentingnya seleksi. “Tidak semua hal harus diubah. Bagian-bagian yang menjadi roh Opera Batak harus tetap dipertahankan,” ujarnya mantap.
Penonton masa kini membutuhkan visual yang kuat. Kostum, tata rias, dan properti diperhatikan dengan detail, sehingga karakter seperti dukun atau ompung [kakek atau nenek] langsung dikenali penonton. Cerita tradisional tetap menjadi dasar tetapi naskah diolah secara kolaboratif, diberi sentuhan humor dan kejutan untuk menjaga keterlibatan penonton sepanjang pertunjukan.
Cermin Zaman
Opera Batak bukan sekadar panggung, musik, atau lakon. Ia adalah cermin sebuah zaman, potret kebudayaan yang pernah hidup begitu meriah di tengah masyarakat.
Namun, perjalanan panjang itu kini berdiri di persimpangan. Di satu sisi, ada kenangan masa kejayaan yang tak ingin dilupakan. Di sisi lain, ada tantangan zaman yang memaksa adaptasi.
Opera Batak membutuhkan lebih dari sekadar pementasan ulang, kesenian ini perlu ruang hidup yang relevan, metode pewarisan yang terencana, dan komitmen bersama antara seniman, akademisi, pemerintah, serta generasi muda.
Seperti alunan uning-uningan [musik tradisional yang mengandalkan kecapi dan seruling] menjelang penyingkapan tirai pertunjukan, setiap upaya revitalisasi adalah tanda bahwa panggung belum sepenuhnya gelap. Masih ada nada yang bisa dimainkan, masih ada cerita yang bisa diceritakan ulang. (Tamat)
Penulis: Patrik Damanik dan Rizal Tanjung
Editor: P. Hasudungan Sirait